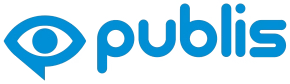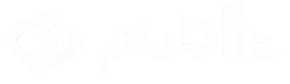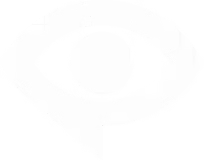PUBLIS.ID, SITUBONDO – Langkah Masir tertatih saat digiring keluar dari sel Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo. Usianya 71 tahun. Rambutnya memutih, punggungnya membungkuk, dan sorot matanya menyimpan lelah yang panjang.
Kakek asal Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo itu kini menyandang status terdakwa. Bukan karena korupsi, bukan pula kejahatan berdarah, melainkan hanya karena lima ekor burung cendet.
Masir didakwa mencuri burung cendet di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Baluran. Secara normatif, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai sah. Hukum berjalan sebagaimana bunyi pasal. Namun, di luar ruang sidang, publik mempertanyakan, adilkah hukum ketika diterapkan tanpa menimbang kemanusiaan?
“Kalau hukum hanya membaca pasal tanpa melihat manusia di baliknya, maka keadilan bisa kehilangan maknanya,” ujar Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat membesuk Masir di rutan.
Kunjungan Nasim Khan menjadi titik balik perhatian publik. Ia duduk berdampingan dengan Masir, mendengar langsung cerita kakek renta yang hidup dalam keterbatasan. Burung-burung itu, menurutnya dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Beliau ini kakek, usianya sudah 71 tahun. Burung cendet itu bukan satwa dilindungi. Nilai ekonominya pun sangat kecil. Tapi ancaman hukumannya dua tahun penjara. Di sini nurani kita diuji,” kata Nasim Khan.
Kasus ini segera melampaui status perkara hukum biasa. Ia menjelma menjadi cermin buram sistem peradilan pidana, antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif.
Di satu sisi, negara wajib menegakkan aturan di kawasan konservasi. Di sisi lain, publik bertanya tentang proporsionalitas tentang apakah hukum telah terlalu keras pada mereka yang paling lemah.
“Penegakan hukum seharusnya tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik,” lanjut Nasim. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.
“Restorative justice itu bukan berarti membebaskan pelanggaran, tapi mencari keadilan yang memulihkan, bukan menghukum secara membabi buta.” tambahnya.
Fakta bahwa burung cendet bukan termasuk satwa dilindungi semakin menguatkan argumentasi publik. Banyak pihak menilai, negara tampak begitu tegas pada rakyat kecil, namun sering terlihat ragu ketika berhadapan dengan kejahatan berskala besar.
Kasus Masir menambah daftar panjang perkara-perkara kecil yang menyentuh rasa keadilan publik. Dari sandal jepit, buah kakao, hingga kini lima ekor burung cendet. Polanya nyaris sama hukum berjalan lurus, tetapi melukai rasa.
“Negara tidak boleh kalah oleh formalitas,” tegas Nasim Khan. “Hukum harus memberi perlindungan, terutama kepada mereka yang rentan.”
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum. Akankah kasus ini diselesaikan dengan pendekatan restoratif, atau justru menjadi preseden lain tentang wajah keras hukum terhadap rakyat kecil?
Di balik jeruji besi, Masir menunggu. Bukan hanya menunggu putusan, tetapi menunggu apakah keadilan masih memiliki ruang untuk berempati. Lima burung cendet itu telah terbang jauh, meninggalkan satu pertanyaan besar yang menggantung di udara: untuk siapa hukum sebenarnya ditegakkan?